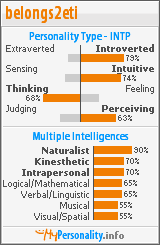“Beth... Bethari,”
Panggilan itu... panggilan itu sangat kukenal. Aku menghentikan langkah. Menengok ke arah suara yang memanggilku. Kulihat sesosok lelaki berdiri di ujung lorong, dekat ruang ICU. Mengenakan jubah Pastor, tangannya menggenggam Alkitab dan Rosario. Lelaki itu lalu perlahan berjalan ke arahku.
“Radheya?” ucapku tak percaya. Kupertajam penglihatanku ke arahnya. Iya, itu benar dia. Wajah oval dengan rambut ikal, mata sayu, hidung mancung dan bibir tipisnya.
Radheya berhenti dua langkah di depanku. Tangannya terulur padaku, akupun menjabat tangannya, meski agak ragu.
“Apa kabar Beth?” tanyanya setelah usai berjabatan tangan.
“Eh.. aku baik. Hmm... “ jawabku kaku.
“Panggil Radheya aja, seperti biasanya kamu memanggilku.” Ucapnya seakan tahu maksud hatiku.
“Kamu apa kabarnya Rad?”
“Aku baik. Puji Tuhan. Akhirnya setelah sekian lama kita bisa bertemu lagi. Hmm... sepertinya mimpimu terwujud Beth?” ucapnya seraya memperhatikan baju putih seragam dinasku. “Dr Theresia Bethari Ratri. Cocok banget Beth,” lanjutnya membaca nametag yang tersemat di baju seragamku.
“Makasih Rad, ini wujud janjiku. Masih ingat kan, waktu itu aku berjanji untuk tetap menggapai mimpiku?” Tanyaku
“Iya. Aku ingat...” Radheya mengalihkan pandangan ke bangku-bangku yang berjajar di lorong Rumah Sakit.
Sejenak kami terdiam. Sibuk dengan pikiran masing-masing.
“Oiya, kamu dalam rangka apa di Rumah Sakit ini?” tanyaku setelah mampu menenangkan hatiku.
“Kebetulan ada salah satu jemaah gereja yang dirawat di sini. Tadi kami melakukan perminyakan, karena kondisinya sudah cukup kritis.” jelasnya padaku.
“Di ruang ICU?”
“Iya.”
“Ohh, terus kamu sudah lama kembali ke sini Rad?”
“Aku baru dua bulan di Gereja St. Laurensia. Awalnya aku ditempatkan di Malang sebelum akhirnya diberi kesempatan untuk mengabdikan hidupku melayani di sini. Kembali ke kota ini. Kamu masih misa di St Monica?” tanyanya. “Ahh, masih ingat dia dengan gereja tempat aku dan dia beribadah dulu.”
“Iya, yang dekat dari rumah.” Ucapku sambil melihat jam di pergelangan tanganku. Hampir pukul sebelas siang. “Maaf Rad, aku masih ada kunjungan pasien. Senang melihatmu lagi.”
“Ooh, aku yang mestinya minta maaf, karenaku tugasmu jadi tertunda,” ucapnya dengan nada menyesal, “Datanglah minggu besok Beth, biar kamu ngerasain misa bersamaku.” Tak lupa senyum manis menghias bibir tipisnya. “Oh Tuhan, aku tak tahu apakah harus kecewa atau bahagia, saat kembali melihatnya,” bathinku.
“Semoga tidak ada halangan Rad, tapi aku nggak janji ya,” jawabku gelisah.
“Usahakan,” pintanya memohon.
“Baiklah...akan aku usahakan,”
“Terima kasih. Selamat bertugas kembali Beth.”
“Terima kasih Rad.” Lalu aku permisi menuju ruang Kenanga, tempat aku melanjutkan kunjungan pasien berikutnya.
- - & - -
“Ahh Radheya, setelah aku mulai bisa melupakanmu kenapa kamu hadir lagi dalam hidupku.” gumamku seraya menghempaskan tubuhku di sofa. Hari baru beranjak petang. Kupejamkan mata sejenak, mencoba menghadirkan kembali peristiwa siang tadi. Radheya masih sama seperti dulu, wajahnya, gerak tubuhnya, nada bicaranya, tak banyak yang berubah. Bahkan senyumnya masih sama. Senyum yang telah membuat hari-hariku begitu merindu. Hufff... kucoba hembuskan nafas keras-keras, berharap beban di hatiku ikut terlepas.
Ingatanku melayang beberapa tahun yang lalu, saat pertama kali aku bertemu dengannya. Waktu itu acara retret pemuda-pemudi gereja di Anyer. Saat istirahat, teman-temanku pergi menyusuri pantai atau naik kapal, sementara aku menghabiskan waktuku duduk sendiri di tepi pantai, menikmati desir angin pesisir sambil melihat pemandangan laut lepas.
“Kenapa nggak gabung dengan teman-temanmu?” sebuah suara mengalun merdu di telingaku. Saat itulah aku tersadar, ternyata ada yang duduk di sampingku.
“Heh?” Aku tersentak. Kupandangi lekat-lekat wajahnya.
“Ups, maaf mengagetkan. Namaku Radheya?” tangannya terulur padaku. Bibirnya tersenyum, rambut ikalnya sesekali berkibar ditiup angin.
“Bethari,” jawabku singkat seraya menyambut tangannya.
“Nama yang indah. Orangnya juga seperti dewi, persis seperti namanya Bethari yang berarti dewi.” Ucapnya. Senyumnya tulus tanpa ada maksud menggoda. Kurasakan hangat menjalari pipiku. Aku menunduk menyembunyikan rasa malu. “Kamu suka menyendiri rupanya.”
“Nggak juga, cuma lagi nggak minat gabung dengan teman-temanku. Terus, kamu kenapa nggak gabung dengan mereka?” tanyaku sambil menunjuk ke gerombolan teman-teman yang bermain jetski.
“Hmm... malas ah. Lagi nggak minat juga,” jawabnya menirukan jawabanku. Aku tergelak mendengarnya.
“Sama kalau gitu. Ngomong-ngomong, namamu Radheya. Nama kecil Karna. Lalu...apakah kamu terlahir lewat telinga seperti Kunti melahirkan Karna?” tanyaku semangat.
“Ahaha... menurutmu?” Radheya tertawa memperlihatkan deretan giginya yang rapi. Matanya menyipit.
“Hmm... bisa jadi.” Jawabku ngawur.
“Yang benar saja. Ibuku bisa pecah kepalanya kalau aku lahir lewat telinga he..he..” Dia tersenyum, lekuk kecil di tengah pipi kirinya menambah manis senyumnya. “Ibuku suka dengan sosok Karna yang ksatria dan berpegang teguh pada janjinya, mungkin harapan ibuku agar aku bisa belajar dari sosok panutannya itu. Kamu suka cerita wayang juga ya?”
“Iya. dulu sering didongengin sama mama,”
“Ohh. Lalu kenapa namamu Bethari. Orangtuamu pasti berharap kau menjadi dewi kebanggaan mereka.”
“Ehehe... mungkin. Atau bisa jadi mamaku tahu kalo aku bakalan cantik seperti dewi.” jawabku ngasal.
“Dasar narsis.” Serunya gemas.
“Biarin...wee.”
“Oiya, aku panggil kamu Beth aja ya, sepertinya lebih enak ngucapinnya daripada Tha atau Ri.”
“Beth. Hmm... boleh juga. Lebih keren he..he.. seperti nama barat kedengarannya,” ucapku setuju.
Lalu kamipun tertawa bersama. Sejak itu, hanya satu orang yang memanggil namaku dengan sebutan Beth, dialah Radheya.
- -
Setelah pertemuan retret itu, aku semakin akrab dengan Radheya yang belakangan aku tahu ternyata dia satu tingkat di atasku. Dia kelas dua SMU, sedangkan aku kelas satu. Meski beda sekolah tapi kami sering bertemu, baik dalam kegiatan gereja atau dia yang sengaja main ke rumahku. Membimbingku belajar, main atau sekedar ngobrol. Dia sangat sopan dan santun dalam bertutur. Dia juga melindungiku dan seringkali berperan menjadi kakak bagiku, mungkin karena Radheya terlahir sebagai anak bungsu, sehingga dia menempatkan aku sebagai adiknya.
Kebersamaan dan perhatiannya yang tercurah kepadaku membuatku merasa ada sesuatu yang tumbuh di hatiku. Perasaan sayang (atau mungkin cinta) dan takut kehilangan yang semakin lama semakin subur. Tapi aku tak pernah menunjukkannya, perasaan itu hanya bisa kupendam dan kunikmati sendiri. Aku hanya berharap Radheya pun merasakan hal yang sama dan mengatakannya padaku suatu hari nanti. Hanya itu harapan satu-satunya yang selalu terlantun di setiap doaku.
Hingga suatu hari satu tahun kemudian, tiba-tiba dia datang padaku.
“Beth... minggu depan aku dan keluargaku pindah ke Yogya, kebetulan Ayah ditempatkan di sana. Aku pernah cerita kan, Eyangku sering sakit-sakitan, makanya kami memutuskan pindah ke sana sekalian untuk merawat Eyang.”
“Secepat itu?” hanya itu yang mampu terucap dari mulutku.
“Iya. Karena kondisi kesehatan eyang sudah menurun. Selain itu, posisi kepala cabang di sana juga kosong, jadi Ayah diminta cepat-cepat mengisinya.” Jelasnya padaku, “Akupun harus segera mengurus surat kepindahanku.”
“Tapi kan tinggal satu semester lagi terus kelulusan. Apa nggak nanggung? Mendingan kamu selesain dulu sampai lulus, baru menyusul ke Yogya.” Protesku.
“Nggak Beth, mungkin justru ini kesempatan baikku. Aku bisa mencari informasi tentang Wedabhakti di sana. Jadi aku bisa mempersiapkannya jauh-jauh hari.” ucapnya bersemangat. Aku bagai tersengat mendengarnya. Fakultas Teologi Wedabhakti, itu salah satu sekolah tinggi untuk menjadi Pastor, sama halnya Driyarkara di Jakarta.
“Rad, aku nggak salah dengar kan?” tanyaku lemas.
“Maksud kamu?” wajahnya berubah bingung.
“Wedabhakti...”
“Oohh... Nggak Beth, kamu nggak salah.”
“Kamu tidak pernah cerita sebelumnya...” gumamku lirih.
“Maafkan aku. Aku baru benar-benar yakin enam bulan terakhir ini Beth. Aku memang menginginkan masuk seminari. Keinginan itu muncul saat aku kecil. Waktu itu masih di yogya, di rumah eyang. Di sana aku mengenal Pater Laurentz, pastor dari Belanda. Beliau sangat dekat dengan anak-anak, penuh kasih dan melayani umat dengan tulus. Aku ingin seperti beliau. Awalnya aku menduga motivasiku hanya karena ingin seperti Pater Laurentz, tapi setelah aku beranjak remaja, keinginan melayani itu malah semakin kuat. Sejak itu aku banyak berfikir dan melihat, hingga tekadku semakin bulat untuk mengikuti jejak Pater Laurentz di jalan Tuhan. Kemudian sekitar setengah tahun yang lalu, aku cerita sama ayah, ibu juga kakak-kakakku, awalnya juga mereka mempertanyakan motivasiku, tapi setelah aku menjelaskan kepada mereka, akhirnya mereka menghargai keputusanku. Bahkan Ayah berpesan, agar aku benar-benar menjalaninya karena panggilan Tuhan bukan karena keputusan sesaat semata.” Radheya terdiam, matanya teduh dan raut mukanya tenang. “Maafkan aku Beth. Aku baru memberitahumu sekarang. Momentnya kurang tepat ya, disaat aku harus pergi meninggalkan kamu, teman-teman dan kota ini. Maafkan aku, aku tahu kamu pasti kecewa mendengarnya. Tapi aku yakin kamu pasti mengerti dengan keputusanku.”
Aku tak tahu harus bagaimana dan berkata apa. Yang aku tahu bahwa detik itu, pupus sudah harapanku untuk mendapatkan cintanya.
“Beth... “ Radheya menggeser duduknya sehingga berhadapan denganku. Tangannya meraih tanganku. Aku masih diam termangu, mencoba mencerna penjelasannya yang baru saja kudengar. “Mimpi kita sama kan? Sama-sama ingin melayani, cuma jalannya saja yang berbeda.”
“Iya.” Hanya itu yang terucap dari bibirku. Lidahku rasanya kelu.
“Kalau begitu, gapailah mimpimu itu Beth, sebagaimana aku berusaha menwujudkan keinginanku. Aku akan selalu mendukungmu Beth, meski dari tempat yang berbeda. Berjanjilah padaku.”
Kutatap wajahnya, begitu tenang begitu damai. Bibirnya membentuk senyuman. “Iya, aku janji.” Ucapku lirih. Mulutku terasa kering, mataku panas.
“Makasih Beth. Be a good girl OK.” Suaranya terdengar lega. Direngkuhnya kepalaku ke dadanya. “Aku akan selalu menyayangimu Beth. Kamu tahu itu.”
“Aku juga, bahkan lebih dari diriku sendiri.” Bathinku. Aku terdiam. Tak kuasa menahan perih yang datang mendera. Genangan di mataku menjebol pertahananku. Aku menangis.
- - & - -
“Andai saja dulu aku mampu mengatakannya dan mencegahnya untuk mengurungkan niatnya.” Sudah tiga hari sejak pertemuanku dengan Radheya, kalimat itu selalu menghantuiku seperti alarm yang setiap saat berbunyi di telingaku.
“Tha... kau baik-baik saja?” suara bernada khawatir terdengar di telingaku. Aku tersentak dari lamunan. Kulihat Krishna menatapku gelisah. Untuk beberapa saat aku terdiam, mengumpulkan kesadaranku yang entah untuk berapa lama terserak.
“Eh... Aku baik. No need to worry.” Aku tersenyum, meski tahu pasti terlihat dipaksakan.
“Nggak Tha, tidak biasanya kau begini.” Khrisna menggeleng-gelengkan kepala. “Sudah beberapa hari ini kulihat kau lebih pendiam. Seperti ada yang kau pikirkan.”
“Aku baik-baik saja, hanya kecapekan. Banyak pasien di Rumah Sakit.” Elakku, lalu kuaduk-aduk orange juice untuk mengalihkan kegelisahanku. “haruskah aku bilang padanya kalau aku ketemu lagi dengan Radheya, cinta pertamaku?” bathinku gusar.
“Ayolah Tha, aku tahu kau tidak baik-baik saja.” Wajahnya serius.
Aku menghela nafas. Mencoba bersikap tenang.
“Krish, kau masih ingat tentang Radheya yang pernah aku ceritakan dulu?” tanyaku ragu-ragu.
“Iya, lelaki yang pernah mengisi hatimu.” jawabnya tenang. “Memangnya ada apa dengannya Tha?”
“Selasa kemarin aku tak sengaja bertemu dengannya di Rumah Sakit. Dia sudah kembali ke kota ini. Menjadi pastor untuk gereja St Laurensia.” Aku menatapnya gelisah, kugigit bibirku. “Sejak pertemuan itu, kenangan tentangnya kembali muncul. Aku takut Krish. Aku takut rasa itu tumbuh kembali.”
Krishna meraih tanganku, jemarinya mengusap-usap punggung tanganku. Hal itu sedikit menenangkan aku. Sorot matanya melembut. “Kau tahu Tha, setiap orang mempunyai masa lalu. Kita semua memiliki kenangan akan sesuatu yang pernah mengisi hidup kita dan aku rasa itu wajar. Yang menurutku tidak wajar adalah ketakutanmu yang berlebihan.”
Aku menunduk. Dalam hati aku membenarkan ucapannya.
“Aku tahu itu sulit, karena dia pernah menjadi yang paling istimewa di hatimu. Tapi itu kan dulu. Yang ada saat ini adalah dirimu yang sekarang.” Ujarnya meyakinkanku, “Kau punya kehidupanmu sendiri begitu pula dia. Dia sudah menemukan kebahagiaannya dengan menjadi dia yang sekarang, yang mengabdikan diri di jalan Tuhan. Begitu pula kau Tha, kau pun menemukan kebahagiaanmu sendiri, yang kuharap itu bersamaku.”
Aku mendongak. Kutatap wajahnya. Mataku beradu pandang dengannya, tak ada ragu di sana. Teduh dan tenang.
“Kau benar Krish. Aku harus bisa melupakannya.”
“Bukan melupakannya Tha.” Krishna meralat ucapanku. “Kenangan itu akan selalu ada di hatimu sampai kapanpun. Yang bisa kau lakukan adalah mencoba berdamai dengan hatimu Tha. Yakinkan dirimu bahwa Radheya hanyalah bagian dari masa lalumu.”
“Ingatkan aku kalau aku mulai goyah.” pintaku padanya.
“Selalu. Aku akan selalu mengingatkanmu sampai kau benar-benar yakin.”
“Makasih Krish. Kau sangat mengerti aku. Seharusnya aku tidak melibatkanmu dengan masalah ini. Maafkan aku.”
“Jangan sungkan Tha. Kau mempunyai aku, ingat itu.”
Krishna Diptaraya. Lelaki yang dua tahun terakhir mengisi hatiku. Yang mengajariku mengeja cinta dan makna setia, yang selalu menemaniku merajut mimpi dan berbagi sepi.
“Kau tidak marah padaku kan?” tanyaku hati-hati.
“Kenapa musti marah?.”
“Kau tidak cemburu kan Krish?” tanyaku lagi. Memastikan.
“Gadis bodoh. Untuk apa aku cemburu,” ucapnya tak sabar, mulutnya menahan tawa “Kau lupa ya? Bukannya Radheya itu pastor. Jadi dia nggak berhasrat padamu Sayang.”
Kali ini tawanya pecah. Bahunya terguncang. Tangannya mengacak poni rambutku dengan gemas. Kurasakan mukamu memanas setelah aku menyadari pertanyaan bodohku itu. Akupun ikut tertawa bersamanya.
“Oiya Krish, dia mengundang aku misa minggu besok. Kau mau menemaniku?” tiba-tiba aku teringat undangannya.
“Pasti. Aku akan menemanimu. Aku juga penasaran dengan sosok bernama Radheya itu. Semoga dia tidak lebih ganteng daripada aku.” Ucapnya setengah menggoda. Matanya mengerling padaku. Aku tergelak melihat tingkahnya.
Krishna. Dia selalu saja bisa membuatku tertawa. Membantuku melupakan kegelisahan dan kesedihanku. Aku tak tahu, apa jadinya aku tanpanya.
- & -
Jam tanganku menunjukkan pukul 7.30 WIB ketika aku dan Krishna tiba di gerbang gereja St. Laurensia, kemudian Krishna langsung mengarahkan mobilnya ke lapangan parkir yang terletak di sebelah kiri gereja. Untuk kesekian kalinya aku menarik nafas panjang, berharap bisa meredam detak jantungku yang melaju kencang.
“Jadi ikut misa kan Tha?” suara Krishna memecah kebisuanku setelah beberapa saat kami terdiam di jok masing-masing. Aku mengangguk ke arahnya.
Kemudian kami turun. Krishna menggenggam tanganku dan kamipun melangkah bersama. Kulihat wajahnya tenang dan senyum tipis tak lepas dari bibirnya, sesekali dia menengok ke arahku. Seperti memastikan aku tak berbalik arah. “Kenapa aku harus risau akan kenanganku, sementara aku sekarang memiliki Krishna yang selalu mengisi hidupku. Yang akan selalu bersamaku menyongsong hari esok.” Kupererat genggaman tanganku. Krishna menengok ke arahku dengan penuh tanya. Aku tersenyum penuh arti ke arahnya.
Memasuki gereja, suasana terasa khidmat meskipun misa belum dimulai. Masih ada beberapa bangku yang belum terisi. Aku dan Krishna mengambil tempat di deretan tengah yang kebetulan kosong. Ruangan dalam gereja begitu luas dengan pilar-pilar yang menempel di dinding dengan patung Santa di atasnya. Kemudian relief timbul peristiwa-peristiwa jalan salib juga tergambar di sekeliling tembok bagian dalam gereja. Salib utama berukuran besar dengan tubuh Yesus yang disalib tergantung di tembok tengah altar, sementara bangku kayu cokelat tua dengan bantalan untuk berlutut dan tempat peletakan sakramen serta sakristi berada pada permukaan yang lebih tinggi dari altar di belakang.
Di sebelah kiri altar, pemberkatan sebelum misa kepada para putra-putri altar dan para petugas liturgi agar misa berjalan dengan baik sudah selesai. Kemudian para pelayan Sabda itu menempatkan diri ke tempat masing-masing sesuai dengan tugasnya. Dan saat itu kulihat sesosok Pastor berjalan memasuki mimbar. Dia, orang yang dulu pernah mengisi hatiku. Pastor Vincentius Damar Radheya.
“Bapa, kumohon kuatkan hatiku.”
- & -
Jakarta 2009