Cangkir si Penyair
Malam belum lagi larut ketika dia pulang dengan wajah kusut. Rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai terlihat masai. Setelah menutup pintu, perlahan dia berjalan ke arahku yang diam terpaku disebalik tumpukan buku. Sampai di meja yang merapat ke jendela dia berhenti. Sempat kulihat dia menarik nafas dan menghembuskannya kuat-kuat, seakan berharap beban di pundaknya ikut terangkat. Dan kurasakan bau alkohol yang begitu menyengat. Hmm… sepertinya dia menenggak arak lagi malam ini. Lalu diletakkan tas butut kesayangannya di atas meja dan berlalu begitu saja. Berlalu begitu saja. Tak memperhatikanku. Mengabaikan keberadaanku.
Ah… betapa bodohnya aku. Bagaimana mungkin dia memperhatikan aku, aku bukan sesuatu yang istimewa baginya. Tak seperti kertas dan kanvas yang selalu menjadi tempat menumpahkan isi kepalanya, luapan imajinya. Aku bahkan tak seperti tas kulit bututnya, yang selalu menemani kemanapun dia pergi. Juga tak seperti batang rokok yang setiap saat bisa disulutnya, menghilangkan asam di mulutnya. Aku hanya sebuah cangkir. Ya… cangkir. Aku hanya bisa memberikan kesetiaanku, itupun bila dia masih membutuhkanku. Itu saja. Apa lagi yang bisa kutawarkan padanya?
Kini kulihat dia sudah telentang di ranjang, matanya menerawang. Wajahnya terlihat sangat lelah, sepertinya dia telah melewati hari-harinya dengan susah payah. Akhir-akhir ini memang dia sering terlihat bingung, kadang merenung, terkadang tampak murung. Mungkin memikirkan hidupnya yang semakin sulit, beban yang semakin menghimpit. Atau mungkin dia sedang jatuh cinta, dengan seorang pelacur di luar sana, terus otaknya tak henti berpikir, bagaimana cara membebaskan kekasihnya itu dari rumah bordir. Hmm… entahlah, aku tak bisa mengira-ngira apa yang ada dalam benaknya. Sesaat kemudian kudengar dia mendengkur, semoga saja dia pulas tertidur.
****
Lanang, sebut saja begitu atau begitu biasanya aku menyebutnya. Aku tak tahu siapa namanya dan aku tak berniat untuk menanyakannya. Ah… kalian tahu sendiri kan, aku tak bisa bicara. Aku tak ingat kapan persisnya dia memilikiku. Yang aku ingat waktu itu diam-diam dia memasukkanku ke dalam tas bututnya ketika dia mampir di kedai kopi langganannya. Dan sampai sekarang aku bersamanya. Menemaninya.
Seperti pagi ini, saat dia menyeduh kopi. Kebiasaan yang selalu dia lakukan. Disaat-saat seperti ini aku merasa sangat bahagia, karena aku dibutuhkannya. Ditemani beberapa linting rokok (mungkin ganja), dia akan memulai aktivitas pertamanya dengan berdiam diri di kamar mandi, setelah itu dia akan duduk di bibir jendela, menikmati hangat mentari yang menerobos masuk ke kamarnya. Tapi terkadang dia juga hanya duduk menekur di pinggir tempat tidur. Tak jelas apa pekerjaannya. Terkadang kulihat dia menulis, kadang melukis. Tapi aku tak pernah tahu kisah apa yang ditulisnya atau gambar apa yang dia tuang dari isi kepalanya. Yang aku tahu, dia akan betah berlama-lama memainkan kuas di atas kanvas, menggambar sesuatu yang tak jelas. Lukisan dengan warna muram, seperti menggambarkan sisi hidupnya yang kelam. Dilain waktu kulihat dia menulis puisi dengan menghabiskan berlembar-lembar kertas, lalu dia akan membacanya keras-keras, dengan tangan mengacung, dada membusung. Mungkin dia seorang penyair. Entahlah...
Setelah itu dia pergi. Meninggalkanku dengan ampas kopi masih tertinggal di dasar tubuhku. Selalu begitu.
****
Malam menjelang tapi Lanang belum juga pulang. Sudah beberapa hari dia tak kembali. Mungkin dia tidur di kolong jembatan, di emperan pertokoan atau bisa jadi di tempat pelacuran. Entahlah, orang sepertinya bisa tidur dimana saja, kapan saja. Dan aku tak pernah mencemaskannya, seperti halnya dia tak pernah mencemaskanku. Tapi aku sering memikirkannya, lebih tepatnya merindukannya. Merindukan dia ada.
Seperti malam ini yang begitu lambat merayap, sementara aku terperangkap dalam kamar yang gelap juga pengap. Senyap. Kamar sempit dengan ranjang usang di sudut ruang, kamar mandi di seberangnya dan beberapa lukisan abstrak yang terpasak di dinding yang mulai retak. Ada sebuah lemari kayu didekat pintu, lemari tempatnya menyimpan segala perabotan, mungkin juga kenangan. Aku pernah melihat ke dalamnya, selain tumpukan baju, ada beberapa gulungan lukisan yang diikat jadi satu, juga sebuah kotak beludru, mungkin isinya lembaran masa lalu.
Dan aku masih teronggok kaku disebalik tumpukan buku, bersama lampu baca dan beberapa lembar kertas di atas meja, juga asbak berbentuk segitiga dengan abu yang masih melekat di dasarnya. Diam membatu. O Lanang, kemana kau berpetualang, tak tahukah kau di sini aku sendiri, sepi? Betapa aku semakin merindukannya. Merindukan saat bibirnya menyentuh bibirku, juga jemarinya yang menari-nari di permukaan bibirku. Atau ketika dia menghirup harum kopi yang menguar dari tubuhku. Bisa kucium nikotin yang terhembus bersama nafasnya yang halus. Ah… betapa aku mendamba kehadirannya.
Aku mulai tak berdaya, menahan jiwaku
yang semakin merindu dan ragaku yang kian melemah,
lelah meredam amarah dan menahan kalut yang begitu akut*
Sementara kau pergi begitu saja, tanpa kata
Menjelma sunyi dalam dada
****
Fajar baru saja terbit ketika kudengar pintu menderit, langkah kaki diseret perlahan dan pintu ditutup dengan pelan. Lanang pulang. Seperti biasanya dia berjalan ke arah meja, meletakkan tas butut kesayangannya. Sejenak diam, menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba dia menoleh ke arahku yang teronggok kaku didekat tumpukan buku. Tangannya meraihku, aku membeku. Lalu dia membersihkan ampas kopi yang mulai mengerak di tubuhku, kurasakan lembut tangannya menyapuku, membasuhku. Betapa aku menikmati setiap detik kebersamaan itu.
Tak berapa lama, kopi tubruk kesukaannya sudah terseduh lagi. Kedua tangannya menggenggam tubuhku, seraya duduk di bibir jendela menikmati hangat mentari yang menerobos masuk ke kamarnya. Dari genggamannya aku bisa melihat wajahnya yang tirus, membuatnya terlihat semakin kurus. Lanang, gerangan apa yang kau pikirkan?
Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dia bangkit. Diletakkannya aku di atas meja, lalu dia meraih ponselnya. Kemudian kudengar dia berteriak-teriak marah. Sementara aku tak bisa berbuat apa-apa, hanya diam mendengarkan amarahnya.
Beberapa menit berlalu. Lanang masih berteriak berang, sementara aku mulai gamang. Dari balik tumpukan buku-buku, kulihat ada yang bergerak-gerak mendekat ke arahku. Langkahnya maju mundur, seperti menghitung aba-aba untuk tempur. Dan tiba-tiba, seperti ada yang tercebur. Kurasakan ada yang bergerak-gerak tak tenang, seperti berenang, hingga kopi ditubuhku serasa bergelombang.
Tut..tut..tut…
Telepon terputus. Lanang membanting ponselnya. Sepertinya dia benar-benar murka dengan seseorang di ujung sana. Kulihat dia berjalan mondar mandir tak tenang. Lalu aku disambarnya dan kopi direguknya dengan tergesa. Tapi sedetik kemudian, diam. Pelan aku diturunkannya, ditatapnya dengan seksama, mungkin dia menyadari ada sesuatu di dalam kopinya.
“Dasar kecoa sialan,” rutuknya, sambil melemparku ke dinding.
Praaaaannngg
Sesaat hening. Kurasakan tubuhku remuk dan berserak. Sempat kulihat lanang berlalu dan membanting pintu. Dan aku tak tahu harus berbuat apa, tubuhku hancur dibuatnya. Mungkin inilah akhir pengabdianku, batas kesetiaanku. Sementara itu kulihat seekor kecoa tertelentang tak jauh dariku. Kaki-kakinya bergerak-gerak menggapai udara. Bisa kulihat matanya yang kian meredup, karena badannya tak kunjung menelungkup. Lalu kedua matanya memejam, diam. Sepertinya kecoa itu sudah kehabisan tenaga. Kasihan sekali dia. Semoga saja Tuhan cepat-cepat mengambil nyawanya. Agar dia tak merasakan derita terlalu lama. Juga agar dia tidak berakhir tragis sepertiku. Seperti nasibku.
-tamat-
201109 ; 06.53 am
Pagi, ditemani secangkir kopi
*dikutip dari puisi menunggu, belongs2eti 2008


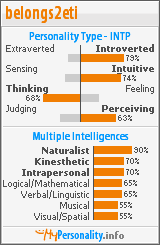
0 komentar:
Posting Komentar