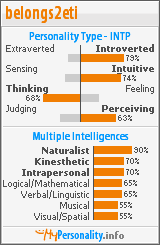Halte
Hari menjelang sore ketika kau langkahkan kakimu keluar dari salah satu pusat perbelanjaan. Seperti biasanya kau menghabiskan waktu di sana, bukan untuk berbelanja apa yang menjadi kebutuhanmu, bukan pula sekedar nongkrong seperti yang dilakukan orang-orang itu. Tapi kau betah berlama-lama di sebuah toko buku. Kau bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membaca di rak buku sastra, dan kau sanggup bertahan bertumpu pada kedua kakimu untuk waktu yang lama.
Kau menengadah, mendung tebal menghias langit sore yang semestinya kelabu. Ah… musim penghujan ini belum berakhir rupanya. Hampir setiap sore selalu turun hujan, membuatmu tak bisa menikmati candhikkala1), fenomena alam yang selalu memesona. Padahal kau berharap seperti yang lalu-lalu, setelah puas membaca kau akan berjalan kaki menuju taman, duduk melepaskan penat sambil menghabiskan soremu dengan menikmati senja, menikmati semburat jingga di cakrawala.
Langit mulai menggugurkan mendung menjadi gerimis. Kau lanjutkan langkahmu menyusuri pedestrian, melewati kompleks pertokoan. Betapa bumi ini makin sesak dengan bangunan-bangunan yang berderet memanjang. Deru mesin kendaraan yang melintas memenuhi telingamu, diselingi suara klakson yang membuyarkan konsentrasimu. Sejenak kau menyesali diri, mengapa tak kau habiskan harimu di rumah saja. Menikmati kesepianmu sendiri.
Tiba-tiba kau teringat satu persatu teman-temanmu yang sudah menikah. Ah… menikah? Tidak. Menikah itu menghabiskan sisa umur kita bersama orang yang sama setiap saat setiap waktu. Banyak temanmu yang bilang, argumen yang kau lontarkan itu tipikal dari seorang pembosan yang belum benar-benar mengerti makna cinta sejati. Bahkan kata mereka, cinta bisa mengatasi rasa bosan. Tapi siapa yang bisa menjamin, selama perjalanan hidup kita takkan muncul rasa bosan. Justru kebosanan-kebosanan itulah yang bisa melunturkan cinta itu sendiri. Dan lagi, menikah bukan semata hanya karena cinta, tapi bagaimana caranya berkompromi dengan egomu untuk menyatukan perbedaan yang ada. Itu yang masih berat bagimu, berdamai dengan dirimu sendiri.
Hujan yang mulai mengguyur memaksamu untuk mencari tempat berteduh. Kau berlari ke arah halte yang kebetulan akan kaulewati. Sesampainya di halte, ternyata banyak juga orang yang senasib denganmu, mencari tempat berlindung dari hujan. Kau kibas-kibaskan rambutmu, dan memilih tempat agak ke belakang, mendekati tiang halte untuk bersandar padanya. Banyak di antara mereka pengendara motor yang terpaksa menghentikan lajunya, ada juga yang penumpang yang menunggu kendaraan yang akan mengangkut mereka ke tujuan, dan ada juga pejalan kaki sepertimu. Lalu matamu tertumbuk pada seorang gadis yang berdiri di ujung halte. Arah tigapuluhlima derajat dari sisi kananmu. Gadis itu semampai dan berambut panjang terurai. Mungkin umurnya sekitar duapuluhan. Selebihnya kau tak perdulikan. Kau mulai sibuk bertanya, berapa lama kau harus berdiri dan pasrah menatap hujan yang rebah ke tanah.
Sudah hampir satu jam kau berdiri, dan hujan belum juga berhenti. Sementara kendaraan datang silih berganti, menaik-turunkan penumpang. Tapi gadis itu tetap bergeming di tempatnya. Kau mulai penasaran dibuatnya. Kau lihat gadis itu diam, matanya menatap lurus ke arah jalan. Oh tidak, seperti lebih dari itu, menembus derasnya hujan. Andai saja kau bisa mengajaknya bicara, pasti kau akan bertanya kenapa dia bertahan begitu lama.
Apa yang kau tunggu di antara rintik hujan yang jatuh, serupa jeruji langit yang mengelilingi tubuh? Seakan membaca pikiranmu gadis itu menoleh ke arahmu. Kau tergeragap. Menggaruk-garuk kepalamu yang tak gatal untuk menutupi kegugupanmu, lalu kau alihkan pandang ke arah jalan yang kini mulai penuh dengan genangan. Titik-titik hujan yang jatuh membentuk lingkaran-lingkaran yang saling bersinggungan. Lalu buyar, mengalir ke sisi jalan dan berebut masuk ke dalam selokan.
Mungkin dia memang sedang menunggu kekasihnya, seperti Shinta yang menunggu kedatangan Rama untuk membebaskannya. Membebaskan dari hujan yang mengurung tubuhnya. Sejenak kau tersenyum, membayangkan dirimu menjadi Rahwana. Raksasa dengan sepuluh muka yang mengurung Shinta, mendamba cintanya. Hingga mau melakukan apa saja agar bisa memilikinya, termasuk menculiknya dari sisi Rama, kekasihnya. O, tidak. Kau hanya mengambil apa yang dijanjikan Dewa, Dewi Widowati yang kau puja yang menitis di dalam tubuh Shinta.
O, Shinta, kenapa kau mau bertahan untuk sesuatu yang sia-sia. Tahukah kau bahwa Rama, ksatria yang kau agungkan itu bahkan tak berani merebutmu langsung dari tanganku. Ksatria macam apa dia, yang meragukan kesetiaanmu, menyangsikan kesucianmu? Dan lagi, kenapa titisan wisnu yang sakti itu tak jua menjemputmu, sementara kau begitu tabah selama dibelenggu. Kemana saja dia selama kau menanggung derita? Bukankah ia hanya seorang laki-laki dengan sayap keperakan dan berbedak cahaya bulan? Ia laki-laki yang takut hujan!2)
Suara klakson mobil membuyarkan lamunanmu. Kau mengutuki dirimu, kenapa bisa berkhayal sejauh itu, melintasi zaman yang begitu purba. Kau lihat sekeliling, hujan berhenti menyisakan gerimis halus. Para pengendara motor yang berteduh sudah mulai meneruskan perjalanannya. Orang-orang juga mulai berlalu, pergi ke tujuannya masing-masing. Kau lihat arloji, hampir pukul enam sore. Saatnya kau pulang. Sesaat kau lihat gadis itu lagi, masih dengan posisi yang sama seperti saat kau tiba. Tapi kali ini wajahnya menunduk. Kau ayunkan kakimu meninggalkan halte, meninggalkan sebuah tanya untuk gadis itu. Mungkin memang benar dia sedang menunggu. Dan sepanjang perjalananmu pulang, pertanyaan itu kembali terngiang. Apa yang kau tunggu di antara rintik hujan yang jatuh, serupa jeruji langit yang mengelilingi tubuh?
170611 ; 09.57pm
catatan kaki :
1) candhikkala : senjakala, gurat merah di langit senja (kamus bahasa sansekerta)
2) Bait puisi Asmara Sinta Asmara Rahwana – Ganug Nugroho Adi.