Kang Sastro
Kamar kontrakan paling ujung itu masih tertutup rapat. Lampu bohlam lima watt yang tergantung dalam ruang itu masih tampak menyala, terlihat dari lubang udara tepat di atas pintu yang menghadap ke utara. Sudah dua hari ini Kang Sastro, penghuni kamar itu tak terlihat, mungkin dia pergi di malam gelap ketika semua penghuni kamar khusyuk terlelap. Lalu pulang menjelang fajar kemudian dia diam mendekam dalam kamar. Mungkin dia tidur? Entahlah…
***
Kang Sastro, begitu orang-orang memanggilnya. Usianya kira-kira hampir empatpuluh tahun. Aku tahu namanya dari ibuku, katanya orang-orang sini tidak pernah tahu siapa nama aslinya, cuma suatu kali dia pernah berkata kalau dirinya itu bukan buruh atau pedagang seperti kebanyakan penghuni kontrakan yang lain, tetapi dia senang sama yang namanya seni, makanya pekerjaannyapun tidak tentu alias serabutan. Kata ibuku, dia pernah melihat Kang Sastro ngemper di dekat stasiun jadi pelukis, pernah juga melihatnya ngamen di terminal nembang geguritan campursari, juga adakalanya baca puisi yang ia tulis sendiri. Pernah juga tetangga kontrakan melihatnya main tobong, ludruk, atau jadi penabuh kendang di acara tayub-an, pokoknya apa saja yang penting nyastro katanya. Ditambah penampilannya yang nyentrik mirip seniman, maka orang-orang memanggilnya Kang Sastro seperti yang aku tahu sekarang. Bisa jadi memang dia seniman.
Kang Sastro itu agak tertutup orangnya, aku jarang melihat dia ngobrol dengan para bapak yang suka kumpul malam-malam di warung kopi di mulut gang. Aku juga jarang melihatnya bercengkrama dengan penghuni kontrakan yang lain. Aku lebih sering melihatnya terdiam, tak banyak bicara tapi tangannya bekerja, kadang menulis atau melukis sesuatu. Tapi anehnya, dia senang bercerita untukku. Dia akan cerita apa saja, dan aku betah berlama-lama mendengarkannya. Kadang dia mendongeng legenda Timun Mas, Joko Tarub, Ajisaka, Ande-ande Lumut, Sangkuriang, juga cerita rakyat lainnya. Kadang tentang lakon tobong atau ludruk yang baru saja dimainkannya. Tapi terkadang dia juga cerita tentang perjalanan hidupnya. Aku tak tahu kenapa dia begitu terbuka padaku, mungkin dia percaya padaku, dia yakin aku tidak bakat jadi penyebar isu. Terlebih lagi, mungkin karena aku bisu, dan itu alasan yang paling masuk akal bagiku.
Pernah dia bercerita tentang istrinya yang katanya dulunya kembang desa di kampungnya yang pada akhirnya pergi meninggalkannya karena tidak mampu bertahan dengan gaya hidupnya, dengan kemiskinannya. Juga tentang anak perempuan satu-satunya yang menderita leukemia yang akhirnya meninggal dunia karena tak ada biaya untuk pengobatannya, bahkan untuk biaya pemakamannya. Lalu kepergiannya merantau ke Surabaya demi menghapus segala kenangan tentang masa lalunya yang begitu menyakitkan baginya. Pun tentang hubungannya dengan pemain tayub yang katanya janda beranak dua yang ditinggal pergi oleh suaminya yang akhirnya mendekatkan keduanya karena merasa sama-sama senasib ditinggalkan oleh orang yang mereka cinta. Semuanya dia ceritakan padaku, pada kebisuanku.
Tapi tatkala Kang Sastro sedang tidak ingin bercerita, maka aku akan menemaninya menulis maupun melukis. Aku akan duduk di dekat pintu, menyandar sambil memeluk lutut. Lalu kang Sastro dengan tekun mengerjakan pekerjaannya tanpa suara. Diam. Dan itu bisa berlangsung berjam-jam. Sering aku berkhayal untuk menepis kebosanan. Ketika Kang Sastro sedang asyik menulis, kubayangkan tiba-tiba dia membeku dan ada yang retak di kepalanya, lalu huruf-huruf berjejalan berebut keluar dari dalamnya. Ada yang melompat, ada yang terbang, ada pula yang meluncur berpegangan pada rambut panjangnya. Lalu mereka semua akan berkumpul di atas selembar kertas di atas meja, menari-nari membentuk formasi, membentuk rangkaian kata. Tanpa pena.
Atau manakala dia sedang melukis, kubayangkan warna-warna menganak sungai keluar dari mulutnya, hidungnya, telinganya bahkan dari kedua matanya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Warna-warna pelangi itu dengan teratur mengalir mengikuti alur tangannya dan berakhir di kanvas di hadapannya. Mereka saling memuncratkan diri ke atas kanvas, membaur -tak teratur, membentuk gambar-gambar abstrak yang sarat gradasi warna. Tanpa kuas.
Dan khayalanku akan berakhir dengan sendirinya manakala kudengar teriakan ibu yang memanggil namaku. Yang merupakan tanda bahwa ibu sudah pulang dari berjualan di pasar, dan aku harus segera pulang menemuinya. Seperti biasanya Kang Sastro akan tersenyum lalu berbicara pelan padaku “Wis nduk, pulang sana. Ibumu pasti membawakan banyak jajanan untukmu.” Aku hanya mengangguk dan beranjak pulang dengan tergesa. Meninggalkannya.
***
Bunyi gaduh membangunkan tidurku dan kulihat ibu sudah tak ada di sebelahku. Langsung aku menghambur keluar ke tempat kegaduhan itu berasal. Sejenak aku terhenyak, hari masih gelap tapi kenapa banyak sekali orang-orang berkerumun di depan kamar kontrakan Kang Sastro. Terus ada Pak RT dan Pak Tarno si pemilik kontrakan. Aneh, tidak biasanya begini. Pasti ada sesuatu yang terjadi.
Kucoba mencari-cari sosok ibuku di antara kerumunan itu. Kulihat ibu berdiri di depan kamar Budhe Sumi yang letaknya tepat di sebelah kamar Kang Sastro. Aku langsung berlari padanya. Ibu sertamerta memelukku dan berbisik kalau Kang Sastro sudah tiada. Katanya lagi, Budhe Sumi curiga karena mencium bau busuk yang menyengat dari kamar Kang Sastro, lantas dia melapor ke Pak Tarno -pemilik kontrakan. Makanya Pak Tarno meminta bantuan bapak-bapak untuk mendobrak pintu kamar Kang Sastro. Dan setelahnya mendapati Kang Sastro tergeletak sudah tak bernyawa. Setengah tak percaya, aku berlari menerobos kerumunan itu. Sesampainya di pintu, aku terpaku.
Kulihat tubuh Kang Sastro tergeletak seperti yang diceritakan ibu. Diam, layaknya orang yang pulas tertidur. Kulihat ada sesuatu yang mengalir dari mulutnya, hidungnya, telinganya bahkan dari kedua matanya. Cairan kental berwarna pekat. Tapi bukan warna-warna pelangi yang sering kubayangkan. Bukan pula hitam. Tapi darah.
-tamat-
akhir maret 2010


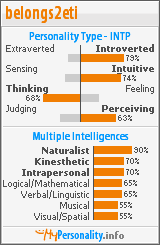
0 komentar:
Posting Komentar