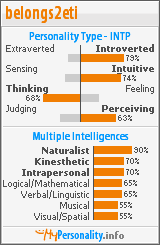Kenangan Hujan
Sisa hujan siang itu menyisakan genangan di beberapa ruas jalan. Travel yang membawaku kembali ke Jakarta penuh penumpang, maklum libur akhir pekan. Mungkin sebagian dari mereka adalah para pekerja di Jakarta yang setiap minggu pulang ke rumahnya di Bandung, dan sebagian lagi mungkin sekedar mengisi liburan dengan kegiatan berbelanja di beberapa Factory Outlet dan Distro yang banyak tersebar di sana. Sementara aku ke Bandung dalam rangka mengunjungi ibu mertuaku. Dulu kegiatan ini sering kulakukan bersama suamiku, tapi entah kenapa akhir-akhir ini ada saja kegiatan di saat bersamaan, jadi terpaksa aku berangkat ke sana sendirian.
Travel baru saja melintasi gerbang tol Pasteur ketika kulihat arloji menunjukkan pukul 5.20 sore. Beberapa penumpang terlihat ada yang mulai tertidur, ada yang sibuk dengan ponselnya, ada juga yang ngobrol santai dengan penumpang di sebelahnya. Kebetulan tempat dudukku di jok paling belakang, di pinggir, sehingga aku bisa menikmati pemandangan sepanjang perjalanan dari balik kaca mobil.
Memasuki Purwakarta, rinai kembali berderai. Sepanjang sore hujan memang berhenti, tapi mendung seakan enggan pergi. Tetap menggelayut. Kini gumpalan awan-awan itu pun kembali luruh, membentuk kristal-kristal bening yang jatuh. Dan aku, begitu menikmati pemandangan itu. Butiran-butiran kristal yang pecah di kaca. Saat-saat seperti ini aku jadi teringat ketika di panti dulu, tempatku menghabiskan masa kecilku. Saat hujan menyapa, seperti biasa aku akan terduduk diam di dekat jendela, menatap langit, mencoba membaca dan memahami pesan yang terbawa bersama butiran-butiran air yang meresap ke tanah. Atau ketika tak juga kupahami, aku akan pergi ke tanah lapang yang letaknya persis di halaman belakang. Berlari-lari kecil ke arah tengah. Lalu aku akan berdiri tengadah. Menantang langit. Meresapi setiap tetesnya yang menimpa tubuh kecilku. Kesenangan itu akan terhenti tiba-tiba ketika kudengar teriakan Laksmi –teman sekamarku- memanggil-manggil namaku, menandakan bahwa Bu Tini -pengasuh panti- melakukan pemeriksaan ke seluruh asrama.
Kilat yang menggores langit membuyarkan kenanganku. Sesaat kemudian guntur terdengar bergemuruh, gaungnya terasa merayap semakin jauh. Kulihat hampir semua penumpang pulas tertidur, sedang Pak sopir tampak konsentrasi mengemudi, menerobos deras hujan yang luruh bagai jeruji. Kuambil ponsel di dalam tas dan mencoba menelpon suamiku untuk mengabarkan kepulanganku, tapi tidak ada respon. Mungkin sedang berkendara. Dia memang ada kegiatan sastra di daerah Bulungan pada siang harinya. Dan panitia memintanya tampil untuk membacakan karya. Beberapa hari yang lalu dia sempat bercerita padaku, untuk pementasan kali ini dia akan membawakan salah satu puisinya dengan gaya teaterikal, gerak puisi demikian istilah dia untuk menyebutnya. Kolaborasi dengan beberapa teman teaternya. Membayangkan pementasannya seperti menggali ingatanku saat pertama kali bertemu dengannya dulu.
Kami berkenalan di suatu acara yang diadakan salah satu komunitas sastra di Jakarta. Waktu itu aku terpana melihat penampilannya di atas panggung. Betapa pembacaan puisinya begitu menyihir orang-orang yang melihatnya, tak terkecuali aku. Dari sana akhirnya kami berkenalan, kemudian berlanjut dengan saling bertukar nomor telepon dan sepakat untuk bertemu di kegiatan-kegiatan sastra berikutnya.
Hingga suatu malam di pertemuan ketiga, ketika aku diantarkannya pulang, dia meminta kesediaanku untuk menjadi istrinya. Menjadi istri, pendamping hidup, bukan semata kekasih. Pernyataannya yang serius, membuatku berfikir sangat serius. Kutatap matanya dalam diam, mencari sesuatu yang lebih berbicara dari sekedar kata-kata. Ada binar yang berpendaran. Dan aku yakin, sangat yakin, di sendu bola matanya itu terbias masa depanku. Tanpa proses yang panjang, aku mengiyakannya. Banyak yang beranggapan bahwa aku terlalu gegabah, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tapi sungguh, aku sudah memikirkan semuanya, lengkap dengan segala konsekuensinya. Bahkan ketika aku bersedia menerimanya, di saat itu pula aku siap untuk kehilangannya. Mungkin ini yang Tuhan gariskan untukku, untuk menjalani sisa waktuku dengan menemani pengelana kata-kata itu.
Setelah persiapan yang singkat, tiga bulan kemudian kami menikah. Pernikahan sederhana, hanya dihadiri keluarga dan teman-teman dekat. Setelahnya hidup kami berjalan apa adanya. Mengalir apa adanya. Dia sebagai kepala keluarga dan aku sebagai ibu rumah tangga, mengabdikan seluruh hidupku untuknya.
Tiba-tiba ponselku bergetar. Ada sms masuk. Ternyata dari Laksmi, teman masa kecilku. Dia mengabarkan bahwa bulan depan akan kembali ke Indonesia, ada beberapa dokumen yang harus diurusnya. Dia juga memintaku menemaninya selama di Jakarta, bernostalgia dengan masa lalu, berkunjung ke panti tempat kami dibesarkan dulu. Akhirnya setelah sekian lama menyepi di Lhasa, turun gunung juga dia. Kurasakan bibirku menarik seulas senyum. Pasti akan kusambut dengan suka cita, betapa kerinduanku sudah menggunung sejak kami berpisah di asrama dulu, bertahun-tahun lalu.
Arloji di pergelangan tanganku menunjukkan pukul delapan malam ketika travel melaju di jalan tol lingkar luar Jakarta, mengarah ke Bintaro. Dalam hitungan menit aku akan tiba di rumah. Perjalanan ini terasa lebih cepat dari biasanya, mungkin karena sepanjang jalan aku sibuk merangkai ingatan. Seperti memunguti potongan-potongan puzzle yang tercecer, lalu menyusunnya kembali menjadi gambar yang utuh.
Tak berapa lama, Travel sampai di pangkalannya di salah satu ruko di kawasan niaga di Bintaro. Dari sana aku melanjutkan perjalananku dengan Taksi. Lima belas menit kemudian gerbang perumahan tempatku tinggal sudah terlewati. Taxi mengarah ke blok terakhir dan berhenti di rumah paling pinggir. Aku turun. Lalu taksi itupun berlalu, menghilang dari pandanganku. Sesaat kulihat sekeliling sebelum langkahku mendekat ke pagar dan membukanya. Memasuki halaman rumah, mobil suamiku terparkir di garasi. Sudah pulang rupanya. Tak sabar aku menuju pintu. Tak terkunci. Tapi sepi. Mungkin suamiku sedang di ruang kerjanya. Kuletakkan oleh-oleh titipan ibu mertuaku di meja makan. Lalu aku beranjak ke kamar.
Belum sempat aku membukanya, sayup-sayup terdengar olehku suara pelan dari dalam. Bisikan-bisikan yang disertai rintihan manja. Suara perempuan dan laki-laki di saat bersamaan. Suara laki-laki itu pasti suamiku, aku sangat mengenal suara bariton yang keluar dari mulutnya, tapi suara perempuan itu.... Siapa? Siapa yang telah berani bercumbu di dalam kamarku, kamar pengantinku?! Kurasakan ada yang mendidih di kepalaku. Jemari tanganku menegang lalu mengepal.
Braaakkkk!!!
Kubuka pintu dengan kasar. Sepasang manusia tanpa busana tampak terkejut. Reflek tangan-tangan mereka menarik apa saja untuk menutupi tubuh-tubuh telanjangnya yang berkilat karena keringat. Sesaat aku terpaku, berharap adegan di depan mataku hanya sebuah mimpi buruk di tengah tidurku. Tapi ini nyata, kurasakan perih di dada. Kulihat suamiku berdiri dan tergesa melangkah ke arahku, dari mulutnya keluar penjelasan-penjelasan yang olehku terdengar seperti dengungan tawon yang mengerubung tepat di atas kepalaku. Tangannya mencoba menghalauku untuk keluar kamar.
Aku berontak. Ini tak bisa dimaafkan. Sungguh. Selingkuh adalah wujud pengkhianatan. Dan yang menyedihkan lagi, perbuatan itu dilakukan suamiku di rumah kami, istana yang kubangun dengan kejujuran hati. Kukibaskan tangan suamiku yang mencoba menghalangi, aku semakin merangsek ke dalam, mendekati perempuan itu yang menggigil takut, terisak di sudut. Pucat. Dadaku bergetar, mulutku getir. Kutampar pipinya lalu kuseret ke kamar mandi, tubuhnya meronta-ronta mencoba melepaskan diri. Suamiku yang mencoba melindunginya membuatku semakin kalap, kudorong dia sekuat tenaga hingga tersungkur membentur siku meja. Lalu kakiku menendang apa saja, kaki, tangan bahkan sekujur tubuhnya. Aku tak tahu, kekuatan apa yang merasukiku. Sampai kemudian kulihat dia tak bergerak, hanya mulutnya yang meringis kesakitan. Mungkin ada salah satu tulangnya yang patah, entahlah.
Perempuan itu berteriak histeris, kubekap mulutnya dan kubenamkan kepalanya berulang kali ke dalam bak mandi, hingga lemas tak sadarkan diri. Selesai berurusan dengan perempuan itu, aku melangkah mendekati suamiku. Tubuhnya masih meringkuk di dekat meja, sesekali mencoba berdiri bertumpu pada kedua lututnya. Tangannya menggapai ke arahku yang berdiri beberapa langkah darinya. Rasa bersalah yang terlukis di wajahnya tak mampu meredakan amarahku yang terlanjur tumpah. Cinta yang kupupuk selama ini seketika lumer, meleleh tak berbentuk lagi. Rasa percaya yang coba kutanamkan padanya langsung tumbang. Potongan-potongan gambar kebersamaanku dengannya tiba-tiba terhambur, berputar-putar, melayang mengelilingiku. Pusing. Kepalaku terasa pening. Kugeleng-gelengkan kepalaku, berharap gambar-gambar itu terlepas dari ingatanku.
Aku harus membuangnya. Melenyapkannya.
Kuambil belati yang selalu kusimpan rapi di kotak riasku, di bawah tumpukan peralatan make up, aman tersembunyi. Lalu secepat kilat kubenamkan belati itu ke dadanya. Pelan kuputar gagang belati sebelum akhirnya kucabut dengan hati-hati. Lubang yang menganga langsung teraliri darah segar, menciptakan genangan di lantai kamar. Banjir darah. Kedua matanya mengiba. Tak berkedip. Tetap saja kurasakan perih mendera tatkala kulihat tubuhnya mengejang, setelahnya geming. Hening.
Lelaki itu, suamiku mati di tanganku. Mati dengan caraku.
“Sekarang katakan padaku, Apakah suami yang telah berkhianat dan tidak bisa bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya patut dipertahankan?"
Semua orang yang hadir di ruang sidang itu terdiam. Semua mata tertuju pada sosok perempuan yang duduk gemetar di kursi pesakitan.
***
 Gerimis kecil berjatuhan ketika kakiku menapaki jalan di pemakaman. Pohon-pohon kamboja berdiri rindang, menaungi nisan-nisan yang berderet panjang. Di deret paling ujung, agak menyendiri, tampak olehku sebuah makam yang masih baru. Bergegas langkahku ke sana. Gundukan tanah merah basah dengan taburan bunga yang mulai layu di atasnya. Aku terpaku menatap sebuah nama terukir di nisan yang beku. Nania Salindri.
Gerimis kecil berjatuhan ketika kakiku menapaki jalan di pemakaman. Pohon-pohon kamboja berdiri rindang, menaungi nisan-nisan yang berderet panjang. Di deret paling ujung, agak menyendiri, tampak olehku sebuah makam yang masih baru. Bergegas langkahku ke sana. Gundukan tanah merah basah dengan taburan bunga yang mulai layu di atasnya. Aku terpaku menatap sebuah nama terukir di nisan yang beku. Nania Salindri.
Nania, teman masa kecilku. Dia ditemukan meninggal dalam keadaan sangat mengenaskan, mati bunuh diri dengan cara memotong nadi. Kabar yang kuketahui, sejak dipenjara atas pembunuhan yang dilakukannya, dia mengalami depresi, lalu memutuskan mengakhiri hidup dengan caranya sendiri.
Hening. Desau angin dingin menyergap tubuhku. Langkahku mendekati nisan, seikat bunga mawar putih kuletakkan di atas pusaranya. Mawar kesukaannya. Mawar yang katanya melambangkan perjuangan yang tak henti, meski kini dia telah tidur abadi.
Hujan mulai turun. Butiran-butiran air tercurah menimpa ranting-ranting dan dedaunan kamboja, kemudian memercik menabrak nisan-nisan di pemakaman. Bebatuan dan rerumputan nampak basah. Tubuhku kuyup. Kenanganku kembali ke masa dulu, ke masa di mana aku dan dia pernah menghabiskan masa kecil di panti. Belajar dan bermain bersama. Satu yang selalu kuingat tentangnya, dia begitu mencintai hujan. Dia akan betah berlama-lama menikmati hujan dari bibir jendela, mendengarkan suaranya yang katanya bagai nyanyian kegalauan. Atau di saat yang lain, dia akan berlari ke tengah lapangan, lalu berdiri dengan tangan terentang, wajahnya menatap langit. Matanya terpejam. Diam. Meresapi setiap tetesnya.
Tiba-tiba mataku menghangat. Tak terasa bulir-bulir airmataku berjatuhan tanpa bisa kutahan, mengalir bersama deraian hujan. Dan saat ini aku baru mengerti kenapa kau begitu mencintai hujan. Sebab di dalam hujan tangismu tak kelihatan.
***
sept' 2010
dalam hujan
gambar dicopas dari http://i723.photobucket.com/albums/ww231/scene90215/girl-and-rain-dark-1.jpg